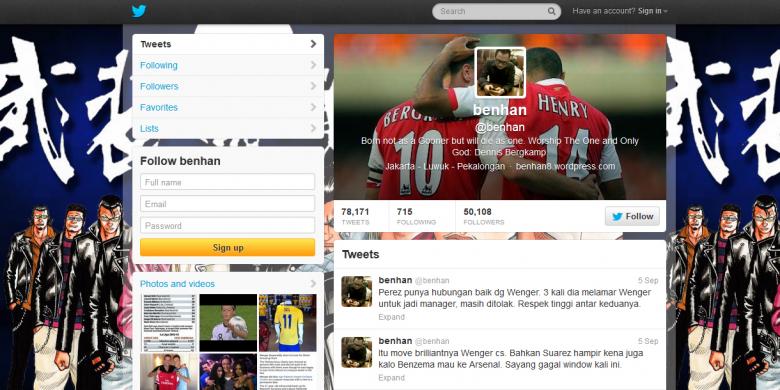Pemberlakuan pasal fitnah,
penghinaan dan pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau
KUHP, sering disorot tajam oleh para praktisi hukum dan praktisi jurnalistik
karena dinilai banyak menghambat kebebasan berekspresi dan menyampaikan
pendapat, khususnya bagi Pers.
Seiring pembahasan RKUHP,
muncul tuntutan dari beberapa kalangan agar pasal pencemaran nama baik dalam
KUHP dicabut, antara lain karena pasal tersebut dianggap ‘pasal karet’ yang
dapat dijadikan alat represif untuk membungkam kebebasan berpendapat. Disebut
pasal karet karena memang sampai kini belum ada definisi hukum di Indonesia
yang tepat tentang ‘apa’ yang disebut dengan pencemaran nama baik sehingga bisa
jadi pasal ini ditafsirkan secara subjektif. Menurut frase (bahasa Inggris),
pencemaran nama baik diartikan sebagai defamation, slander, libel yang dalam bahasa Indonesia (Indonesian translation)
diterjemahkan menjadi pencemaran nama baik, fitnah (lisan), fitnah (tertulis). Slander adalah oral
defamation (fitnah
secara lisan) sedangkan Libel adalah written
defamation (fitnah
secara tertulis). Dalam bahasa Indonesia belum ada istilah untuk membedakan
antara slander dan libel.
Meskipun masih dalam perdebatan, ketentuan-ketentuan tentang penghinaan yang
terdapat dalam Bab XVI, Buku II KUHP masih relevan, oleh karena itu, sebenarnya
pasal ini tidak perlu dicabut. Cukup direvisi dengan diperjelas tafsir dari
pencemaran nama baik itu sendiri.
Ketakutan yang lain dari
pemberalakuan pasal pencemaran nama baik antara lain adalah bahwa pasal
tersebut dijadikan alat untuk mengkriminalisasikan pers. Penerapan pasal
mengenai pencemaran nama baik di Indonesia memang sangat rancu. Pers ataupun
individu yang dituduh mencemarkan nama baik dapat terkena pasal pidana maupun
perdata. Kebanyakan jika penggugat menang dalam perdata, putusan perdata akan
digunakan untuk mengintimidasi di pidana juga, begitu pun sebaliknya.
Parahnya, ketika terjadi delik
pers, para praktisi hukum seperti polisi, hakim, jaksa, pengacara, atau pun
masyarakat umumnya tidak memiliki kesamaan pendapat dalam menjelesaikan kasus
pers. Apakah menggunakan Undang-Undang No. 40/1999 (UU Pokok Pers) atau Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)? Ketidakseragaman pendapat tersebut terbukti
dengan adanya beberapa kasus pers yang diselesaikan melalui mekanisme Hak Jawab
sesuai UU Pers. Tetapi, ada juga kasus pers diselesaikan lewat pengadilan
pidana.
Pasal 5 ayat A2 UU Pers
menyebutkan pers berkewajiban melayani hak jawab dan hak koreksi serta menarik
berita atau tulisan yang salah. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan ini
diancam hukuman denda paling besar Rp500 juta. Dalam prakteknya, pelaksanaan
aturan hak jawab dalam UU Pers menghadapi masalah. Jika media memberikan hak
jawab kepada pihak yang dirugikan oleh suatu pemberitaan, hal itu tidak menutup
kemungkinan korban menggugat atau mengadukan kasusnya ke pengadilan. Maka
revisi yang perlu diusulkan adalah, harus dengan tegas menyatakan “Jika media
sudah menarik kembali berita yang keliru, meminta maaf atau memberikan hak
jawab, maka kasus pencemaran nama baik dapat digugat perdata ke pengadilan,
tapi tidak disertai hukuman pidana”.
Masyarakat pers Indonesia
sendiri terpecah dua dalam memperjuangkan kebebasan pers. Ada yang setuju UU
Pers sebagai Lex Specialis, namun ada pula yang tidak. Ada pula kalangan
menginginkan agar UU Pokok Pers direvisi, agar dapat benar-benar berperan
sebagai Lex Specialis untuk perkara-perkara yg melibatkan pers.
Gagasan merevisi UU Pers ini
tentu sangat tidak populer, terutama di kalangan pers. Namun perlu dipahami
bahwa Revisi UU Pers tidak semata-mata bermaksud mengurangi kebebasan pers dan
meningkatkan kontrol terhadap pers. Justru sebaliknya. Hal-hal yang selama ini
dirasa mengganggu, dapat diatasi dengan Revisi UU Pers. Misalnya, Pasal 7 UU
Pers menyebutkan bahwa setiap wartawan wajib memiliki dan mentaati kode
etiknya. Menurut penulis, pasal ini justru harus dihapus, karena berkaitan
dengan kode etik, dan kode etik adalah urusan organisasi profesi.
Di lain pihak, ada beberapa
hal yang perlu diakomodasikan dalam UU Pers, misalnya obscenity dan indecency.
Jangan sampai ada lagi anggota Dewan Pers mengatakan bahwa tabloid porno dan
yellow paper itu bukan pers. Itu selebaran. Pernyataan ini menunjukkan bahwa
pers ‘angkat tangan’ atau ‘cuci tangan’. Padahal, tidak benar bahwa pers adalah
hanya koran/majalah seperti Kompas dan Tempo. Menurut UU Pers juga, pers adalah
wahana komunikasi massa yang menyampaikan informasi kepada masyarakat dalam
bentuk gambar, suara, tulisan (Bab I, Pasal 1, butir 1, UU Pokok Pers).
Menganggapnya sebagai ‘bukan pers’ adalah sikap yang kurang bertanggungjawab.
Hal lain yang perlu
diakomodasikan dalam Revisi UU Pers adalah kasus-kasus yang selama ini berada
di luar UU Pers sehingga ‘terpaksa’ digunakan pasal KUHP dan menyebabkan UU
Pers tak bisa dipakai sebagai lex specialis. Isu-isu itu antara lain:
pencemaran nama baik, fitnah, berita palsu/bohong, penghasutan, penyebar
kebencian (hate speech), dan hal-hal lain yang memang sering menjadi bagian dari
pemberitaan pers. Dimasukkannya hal-hal ini ke dalam Revisi UU Pers justru
untuk melindungi dan akan menyelamatkan kinerja pers bebas. Karena kasus-kasus
itu, bila muncul, akan disikapi di bawah naungan UU Pers. Tak perlu lagi KUHP
yang ancaman hukumannya berupa hukuman kurungan/penjara. Dalam Revisi itu
hendaknya diatur pula bagaimana mensikapi kesalahan jurnalistik yang mengandung
unsur-unsur tersebut di atas.
Namun itu bukan berarti pasal
pencemaran nama baik dalam KHUP harus dihapuskan. UU Pokok Pers dapat dijadikan
Lex Specialis tentunya tidak dengan mencabut pasal pencemaran nama baik dalam
KUHP. Bagaimanapun hukum pidana itu ultimum remedium, tapi pada prinsipnya
dalam aturan tentu ada logika hukumnya dalam penerpan sanksi. Semoga
kawan-kawan pers dapat memahani ini karena keberadaan pasal-pasal pencemaran
nama baik dalam KUHP tetap di perlukan sebagai fungsi kontrol.